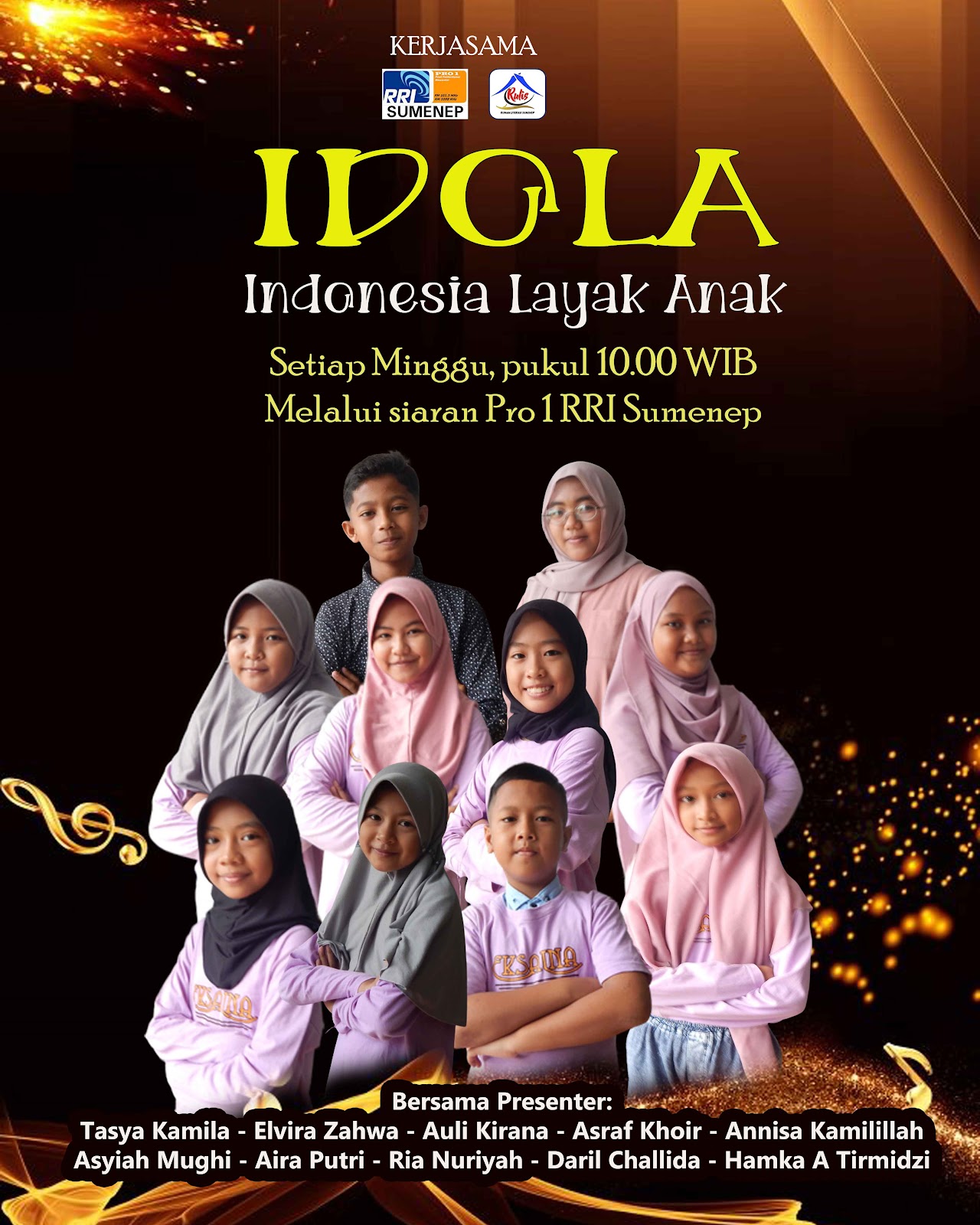Usaha Membandingkan Sastra Islam Dan Sastra Pesantren
Mashuri Alhamdulillah
Ceritanya begini. Saya bermaksud menulis sekilas, tapi dengan hasrat besar dan menggebu-gebu, untuk menguak genealogi dan arkeologi sastra pesantren berdasarkan dengan beberapa data dan penelitian yang telah saya lakukan dengan perspektif pesantren sebagai habitus sastra. Namun, saya terganjal pada sebuah ngablak (terbuka lebar (untuk mulut atau pintu) saya pada tahun 2018-an, tentang sastra Islam. Itu pun hanya sebatas mukadimah dari sebuah tulisan yang diniatkan panjang. Akhirnya, saya membaca ulang ngablak saya dan tersenyum sendiri, ketika otak saya yang tengil bertanya: apa bedanya sastra Islam dengan sastra pesantren? Hmmm. Berikut ini ngablak saya tentang sastra Islam terdahulu, yang belum saya edit dan tambahi referensi. Siapa tahu, ada pembaca yang memiliki cara pandang berbeda berdasarkan acuan yang berbeda pula. Begini nukilannya.
Apa Itu Sastra Islam
Apakah sastra Islam itu? Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi jawabannya sungguh dapat panjang, dalam, dan luas. Bila ditulis dalam sebuah risalah atau kitab, dapat berjilid-jilid banyaknya dan mirip sepur ditumpuk sembilan. Ihwal sastra Islam, sudah tersurat dalam sejarah sastra di dunia cukup banyak para sastrawan, budayawan, ahli sastra dan lain sebagainya yang membahas, menganalisis, bahkan menjadikan pokok soal sastra Islam sebagai bahan polemik dan perdebatan, baik itu polemik kesusastraan maupun polemik kebudayaan. Tentu, dalam konteks yang serba serius demikian, tak elok bila saya menyatakan bahwa sebuah sastra disebut Islam karena sastra tersebut sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ehm!
Dalam sastra Indonesia, terdapat beberapa peristiwa dan pembahasan yang berpusar seputar sastra Islam. Pertama adalah polemik “Langit Makin Mendung” karya Kipanjikusmin pada tahun 1950—an yang membuat HB Jassin, redaktur sastra, dipenjara karena bertanggungjawab pada pemuatan cerpen tersebut tanpa bersedia membuka jati diri pengarang sesungguhnya. Perbincangan kedua terkait tentang sastra pesantren dalam sebuah forum ilmiah dengan pembicara yang diawali oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam sebuah tulisan di media, kemudian direspon oleh Ahmad Tohari, D Zawawi Imron, dan beberapa pendekar sastra lainnya.
Pembicaraan mereka dipantik dengan statemen bahwa sastra pesantren adalah sastra yang ditulis oleh orang berlatarbelakang pesantren tentang dunia keislaman dan pesantren. Ahmad Tohari menyematkan sebuah pernyataan yang mengundang tafsir lebih jauh bahwa sastra pesantren atau Islam itu sastra yang identik dengan dakwah.
Perbincangan ketiga yang langsung menyeruak pada jantung permasalahan dengan bertumpu pada bidang ilmu-ilmu sosial adalah gagasan sastra profetik yang ditelorkan oleh Kuntowijoyo. Ditegaskan, sastra yang berspirit kenabian itu tidak hanya berpatok pada kualitas teks semata tetapi juga diiringi dengan semangat pencerahan dan hasrat perubahan terhadap kondisi masyarakat.
Tidak hanya di Indonesia, di negeri jiran Malaysia juga terdapat beberapa perbincangan. Salah satunya yang kondang adalah polemik sastra Islam pada tahun 1980an di media Dewan Bahasa antara Kassim Ahmad dan Shahnon Ahmad. Yang satu berpegang pada formalisme Islam, sedangkan satunya berpatok pada universalisme Islam. Perdebatan lama itu pun tidak dapat merumuskan sastra Islam yang dapat diterima banyak pihak karena masing-masing memiliki perspektif yang berbeda.
Di dunia Arab, termasuk di Mesir, Libanon, dan lainnya, serta Iran, pembicaraan ihwal sastra Islam memantik diskusi panjang, baik oleh kalangan agamawan, sastrawan, dan kritikus sastra, dan selalu meruncing ke pemahaman para pesastra yang terlibat di dalamnya yang mengusung ideologi tertentu dengan menempatkan sastra sebagai wilayah bebas nilai sekaligus sarat nilai. Termasuk di dalamnya adalah pendirian kreatif sastrawan peraih Nobel sastra tahun 1988 dari Mesir yaitu Naguib Mahfoud, yang sangat hormat pada Universtas Al Azhar, yang secara realistis menyatakan bahwa ia berkarya di atas dua peradaban besar, yaitu peradaban kuno Mesir dan puncak peradaban Islam, dengan tidak dapat mengabaikan pengaruh peradaban Eropa. Selain dia, banyak pula penulis yang selalu mengatasnakaman karyanya sebagai novel Islami dengan penekanan pada pesan dan menjauhi bentuk estetika terutama di kalangan formalis Islam.
Dari berbagai saling-silang di antara berbagai diskursus, dapat ditarik benang merah bahwa ada kalangan yang berada di kubu sastra yang mengunggah nilai-nilai formal Islam, ada yang berada di kubu universal yang mengunggah nilai-nilai Islam yang universal tanpa harus mendaku diri dengan formalitas Islam. Selain itu, banyak pemahaman lainnya, yang hingga kini belum tuntas untuk dibahas dan dirumuskan karena perkembangan sastranya berjalin kelindan dengan warna lokal. Di antaranya adalah merebaknya karya yang bertumpu pada pembumian nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, sebagaimana yang pernah dirintis para penyebar Islam di Indonesia, dengan menggurat karya-karya bermetrum sastra lokal dan dalam bahasa lokal.
Karena saya hanya debu dalam lautan pasir sejarah sastra, saya tak ingin turut dalam kancah tersebut dan memperuncingnya. Saya meyakini bahwa tarekat sastra yang dianut para penulis muslim memang memiliki tujuan-tujuan yang tidak jauh dengan visi keislamannya. Memang, ada yang mendaku karyanya sebagai karya Islami, dengan mengunggah bahasa-bahasa formal Islam, ada pula yang tidak secara formal mendaku sebagai karya Islami tetapi di dalamnya kaya dengan nilai-nilai Islami.
Dalam konteks yang serba mengambang, saya mengambil jalan sederhana dengan mengamini tengara yang disematkan Braginsky, ahli sastra Persia dan Melayu, bahwa dalam sastra Melayu lama itu memiliki kesatupadanan antara bentuk dan isi sebagai karya yang indah, berfaedah dan kamal. Tengara itu lebih sesuai dengan gambaran sastra Islami yang sekaligus menambahi batasan sastra yang digagas Horace yang terlalu lawas bahwa sastra itu dulce et utile, indah dan berguna.
Namun, mohon maaf, dalam kesempatan yang asyik ini, saya tidak akan membicarakan ihwal sastra Islam dalam konteks epistemologis dan ontologisnya, saya hanya ingin menjelajahi berbagai khasanah Islam yang sudah lazim, sekaligus menyingkap adanya keterputusan transformasi pengetahuan perihal sastra Islam dalam sejarah sastra di Indonesia yang dalam kurun waktu sangat lama karena adanya politisasi diskursus terhadap khasanah keislaman di Nusantara, terutama dari pihak kolonial. Bila dalam dunia persilatan, tulisan ini adalah sejenis jurus ngeles atau menghindar dari sergapan. Namun, karena ini dunia persuratan, tentu namanya bukan jurus ngeles tetapi teknik pepatah lama: sambil menyelam buang air, eh minum air.
Demikianlah, penggalan mukadimah makalah yang hingga kini belum tertangani dengan indah, berfaedah, dan kamal.
Sumber: Akun FB Mashuri Alhamdullah